
Wendy Chu: Rasisme, Penyesuaian, dan Lika-liku Melanjutkan Kehidupan di Negara Lain Sebagai Imigran AS Asal Indonesia
Bagi banyak orang, berpindah ke negara lain bukanlah hal yang mudah. Selain harus beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru, berpisah dengan tanah air yang selama ini menjadi rumah tentu membuat hati berat.
Pada 2020, Wendy Chu dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke San Francisco, Amerika Serikat dan menetap secara permanen di sana. Gadis usia 21 tahun ini harus meninggalkan rumah, sekolah, dan teman-temannya di Medan untuk melanjutkan kehidupannya di negara baru. Kini, ia sedang melanjutkan studinya sembari bekerja sebagai guru di waktu luangnya.
Sebagai seorang imigran, banyak tahap yang dilalui dan tantangan yang dihadapi untuk mencapai titik ini. Mulai dari persiapan untuk pindah, perbedaan budaya dan lingkungan, hambatan dalam mencari kerja, serta perlakuan yang diterima dari sekitar sebagai orang luar—Wendy menceritakan pengalamannya sebagai imigran AS asal Indonesia.
Baca juga: Andrea Nathania: Student Filmmaker yang Ingin Menjadi Bagian Revolusi Sinema Indonesia
Pindah untuk Kesempatan Hidup yang Lebih Baik

Banyaknya kesempatan yang dinilai lebih menjanjikan di AS menjadi alasan keluarga Wendy memutuskan untuk pindah ke negara tersebut.
Pada tahun 1900-an, AS mendapat julukan “The Land of Opportunity” yang berarti tanah penuh kesempatan. Banyak orang bermigrasi ke AS untuk mencari peluang kerja dan kualitas hidup yang lebih baik.
Keluarga Wendy pun melihat hal yang sama.
“Orang tuaku mempertimbangkan peluang pendidikanku dan adikku karena sekolah di sana bisa gratis. Ada juga pertimbangan kalau amit-amit kami tidak mendapatkan kerja, masa depan bisa tetap diselamatkan oleh adanya program-program unemployment,” jelas Wendy.
Ia menjelaskan bahwa usia juga membuat keluarganya turut prihatin dengan masa depan.
“Orang tuaku semakin tua,” kata Wendy. “Harus ada jaminan masa tua dan program-program yang membantu hari-hari tua. Di AS, banyak sekali fasilitas dan layanan keuangan yang bisa mendukung.”
Menurut Wendy, Indonesia juga pasti memiliki layanan dan fasilitas yang serupa. Hanya saja, akses di Indonesia jauh lebih sulit dibandingkan akses di AS.
“Aku tahu di Indonesia banyak fasilitas, tapi akses di Indonesia masih susah. Belum lagi banyak masalah tentang program-program yang tidak sampai ke tangan para pendaftar,” ucapnya.
Wendy menceritakan bahwa meninggalkan kota Medan tidak terlalu menyedihkan baginya. Rupanya, ini bukan kali pertama ia harus berpindah tempat tinggal. Sebelum Medan, Wendy sebelumnya menetap di Jakarta.
“Tidak terlalu sedih karena aku sudah pernah mengalami yang namanya perpisahan. Dulu aku tinggal di Jakarta sampai kelas 5 SD, terus pindah ke Medan sampai akhir SMA. Hampir seperti repeating process,” jelasnya.
Namun, rasa kangen dan sedih ternyata baru dirasakannya saat sudah musal tinggal di AS.
Baca juga: Soraya Nathasya: Kisah Penari Balet Indonesia yang Sudah Menari Selama 17 Tahun
Individualisme AS Membuatnya Sulit Bergaul
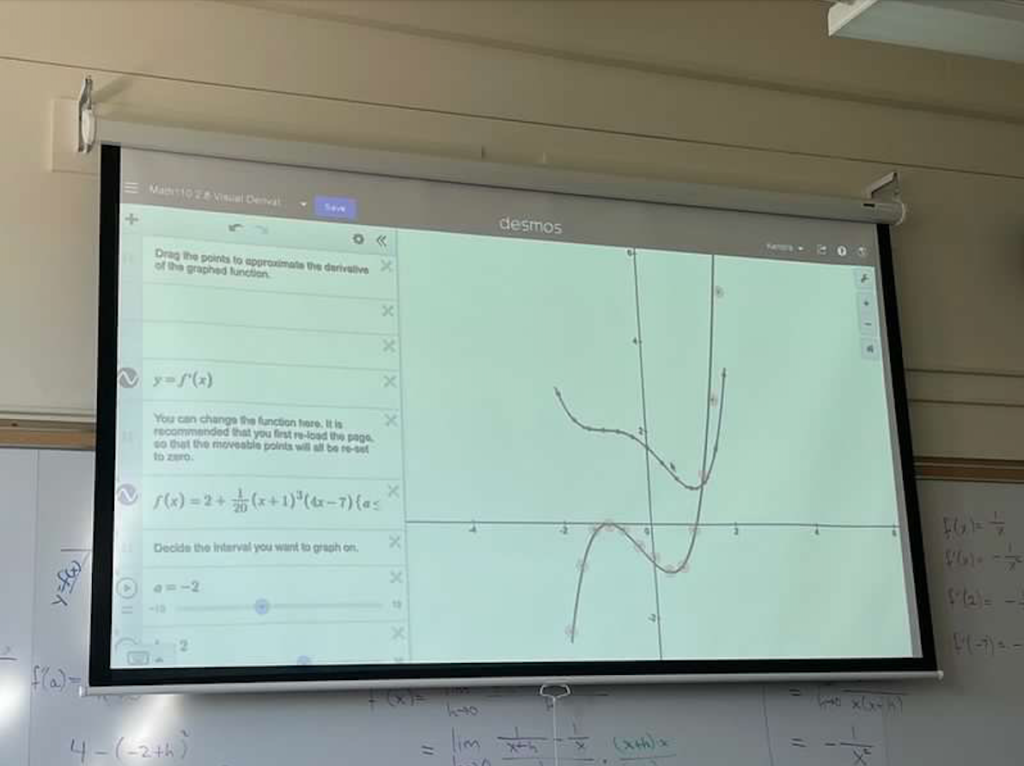
Rumitnya mencari pergaulan menjadi salah satu tantangan yang ia hadapi. Saat berkuliah di sana, sulit bagi Wendy untuk mencari teman yang sejurusan karena kelas-kelas yang mencampurkan mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai program studi.
“Susah mencari teman yang sejurusan denganku dan yang terbuka terhadap pertemanan baru. Waktu itu zaman pandemi dan masih online, jadi makin susah,” katanya.
Selain penempatan kelas, Wendy menduga bahwa sifat penduduk AS yang berbeda dari penduduk Indonesia ketika bersosialisasi merupakan salah satu faktor. Di sana, orang-orang cenderung individualis dan tertutup. Di Indonesia, masyarakatnya lebih mudah berbaur karena budaya kekeluargaan dari timur.
“Di sini susah sekali mendapat teman dekat. Kalau di Indonesia, orang-orang tidak takut untuk saling akrab. Bahkan walaupun aku sudah tinggal di AS, masih ada orang Indonesia yang menanyakan kabar walau kita tidak terlalu kenal,” ucapnya.
Akhirnya, Wendy menemukan dirinya di tengah imigran-imigran asal Indonesia yang juga menetap di wilayahnya, San Francisco. San Francisco terkenal sebagai satu dari beberapa daerah di AS dengan jumlah imigran terbanyak, dengan 31% populasi yang berasal dari luar negara.
“Karena banyak imigran di sana, jadi ada semacam sense of family. Aku sering bertemu dengan imigran dari Indonesia juga,” katanya. “Ya, tapi, aku tetap mencoba untuk keluar dari zona nyaman dan berteman dengan orang-orang yang bukan dari Indonesia.”
Baca juga: Danya Tjokroardi: Aktivis Muda Pembangun Media Digital We The Genesis di Usia 14 Tahun
Sempat Takut Keluar Rumah karena Rasisme

Sebagai pendatang, Wendy tidak jauh dari pengalaman rasis. Asian hate atau kebencian terhadap orang Asia merupakan fenomena yang marak di era pandemi. Kebencian ini memiliki akar-akar yang dalam, tetapi berita mengenai virus COVID-19 yang berasal dari Tiongkok membuat kebencian ini semakin marak.
Berbagai gerakan untuk mendukung dan melindungi hak orang Asia di AS dibuat, mulai dari protes, petisi, hingga kampanye. Namun, semua ini tidak cukup untuk melindungi imigran asal negara-negara Asia, termasuk Wendy sendiri, dari rasisme.
“Waktu itu aku sedang jalan pulang, dan ada orang non-Asia yang mengucapkan hal yang membuatku tidak nyaman kepada diriku,” ceritanya.
Pengalaman tersebut membuat Wendy tidak ingin menginjakkan kaki keluar rumahnya selama beberapa minggu.
“Aku sempat takut untuk keluar selama kurang lebih dua minggu,” kata Wendy.
Ia juga sering melihat berita mengenai insiden-insiden rasis lainnya di media. Mulai dari ujaran kebencian, kekerasan, hingga kejahatan parah. Adanya hal yang serupa terjadi padanya membuat dirinya shock dan merasa tidak aman.
Akan tetapi, insiden itu tidak menumbuhkan rasa benci yang sama di hati Wendy.
“Kalau aku membalas mereka dengan kebencian yang sama, maka aku sama saja rasis. Lebih baik tidak menghakimi dan tidak membuat pengalaman ini jadi bahan untuk menyamaratakan semua orang non-Asia di sana,” tambahnya.
Wendy berharap bahwa kebencian terhadap minoritas dan rasisme di AS akan berkurang di masa depan.
Baca juga: Bella Fedora: Lika-liku Sebagai Model Hingga Jadi Finalis Puteri Indonesia Jawa Tengah
Etos Kerja AS Tidak Seramah Indonesia

Kini, Wendy sedang mengambil program studi pilihannya di City College of San Francisco (CCSF), jurusan Psikologi. Sembari meneruskan pendidikannya, Wendy juga bekerja sebagai guru anak-anak sebagai bagian dari program kegiatan yang dilakukannya setelah kelas-kelas mata kuliah.
“Di sini, ada yang namanya After School Program. Aku memilih untuk mengisi program tersebut dengan mengajar anak-anak. Semua muridku rata-rata dari TK hingga kelas 5 SD,” jelasnya.
Profesi ini bukan pekerjaan pertama Wendy. Setibanya di AS, Wendy sudah pernah bekerja di beberapa tempat.
“Pertama, aku kerja di Amazon sebagai shopper. Sederhananya, aku bantu packing pesanan-pesanan orang di warehouse,” kata Wendy.
Ketika masih menjadi shopper, keseharian Wendy dipenuhi oleh kegiatan di warehouse Amazon. Ia membantu pengemasan barang-barang pesanan ke dalam kardus dan bahan kemasan lainnya. Barang-barang tersebut pun tidak bisa dikemas dengan sembarangan.
“Packing sendiri ada ilmunya. Ada urutan barang-barang yang masuk ke dalam kardus, berdasarkan beratnya. Benda-benda fragile ada caranya sendiri untuk di-packing,” ceritanya.
Kemudian, Wendy bekerja di toko teh boba.
Di pekerjaan tersebut, Wendy menemukan bahwa etos kerja di AS juga berbeda dari yang ada di Indonesia. Di usaha-usaha makanan dan minuman Indonesia, pelanggan yang salah memilih pesanan tidak bisa mengubah apa yang sudah dipesan setelah makanan atau minuman sudah dibuat. Hal ini tidak berlaku di AS.
“Customer boleh meminta karyawan untuk membuat makanan atau minuman beberapa kali sampai menurut customer enak. Harga yang dibayar pun tetap harga normal. Sebagai karyawan, ini melelahkan.”
Diskriminasi pekerjaan lebih jarang ditemukan di AS ketimbang di Indonesia. Di sana, pekerjaan adalah pekerjaan terlepas dari pendapatan dan tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Di Indonesia, pekerjaan-pekerjaan yang hanya sebatas upah minimum atau di bawah upah minimum sering dipandang rendah.
“Di sini, aku cuma jadi shopper di gudang atau penjaga toko teh pun tidak masalah. Di Indonesia, mungkin aku bisa dihujat tante-tante.”
Baca juga: Venezia Guishella: Tantangan Seorang Seniman Modern di Tengah Negara yang Minim Apresiasi Seni
Berencana untuk Menjadi Konselor Anak

Wendy Chu (FOTO: Wendy Chu) 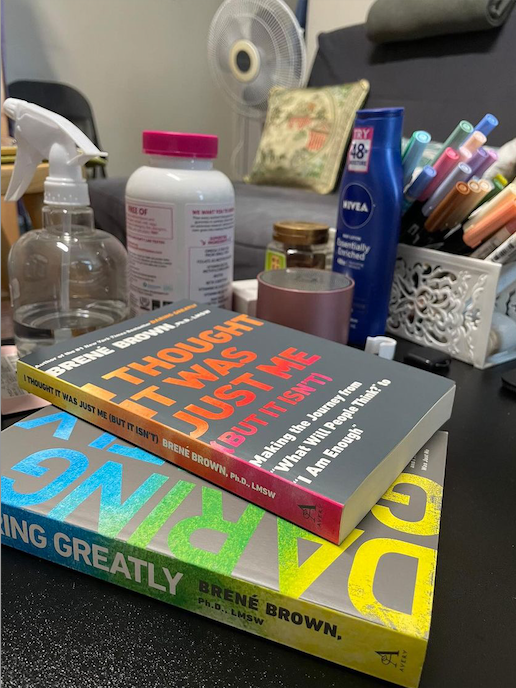
Buku-buku yang dibaca Wendy. (FOTO: Wendy Chu)
Wendy memiliki impian untuk menjadi psikologis atau konselor yang dapat membantu orang. Pekerjaannya yang sekarang sebagai seorang guru menemukan kegembiraan dalam bekerja dengan anak-anak, tetapi ia merasa bahwa menjadi guru bukanlah panggilannya.
“Sejak jadi guru, aku jadi suka anak-anak. Aku suka sekali membantu mereka berkembang, tapi aku tidak mau jadi guru,” bicara Wendy. “Aku lebih cocok jadi konselor atau terapis anak.”.
Wendy bertekad untuk terus berjuang dan berusaha dalam semua yang dilakukannya. Ia bersikap optimis terhadap masa depannya dan tidak takut merangkul kesempatan apa pun yang lewat.
“Selama aku terus berusaha dan memberikan sepenuh hatiku, aku rasa aku akan baik-baik saja.”
Wendy Chu bukan satu-satunya perempuan inspiratif yang dihadapi oleh tantangan-tantangan hidup. Baca cerita-cerita perempuan lainnya yang tidak kalah hebat!
Mau berbagi pengalaman hidupmu? Bergabung ke Girls Beyond Circle sekarang!
Comments
(0 comments)